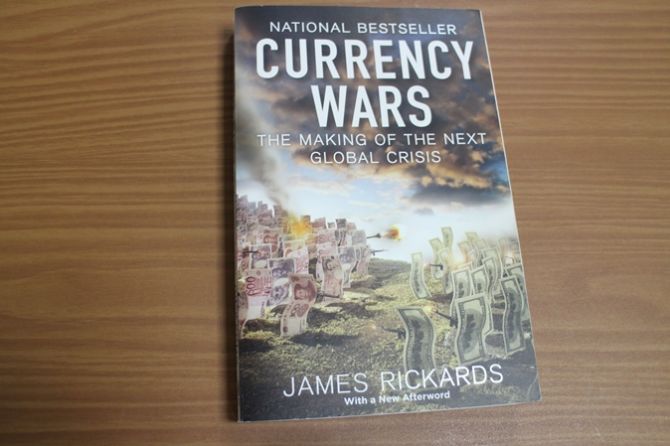
Currency Wars
Muh.Ishak | Resensi Buku | Wednesday, 18 March 2015
MENGAKHIRI PERANG MATA UANG
Perang mata uang memang tidak melibatkan barisan tentara dan ledakan mesiu. Meskipun demikian, efeknya dapat jauh lebih dahysat dari perang militer, baik dari jumlah korban maupun kerugian materil. Melonjaknya harga pangan tahun 2010 silam yang kemudian menyebabkan kelaparan di berbagai belahan dunia bahkan memantik revolusi berdarah di kawasan Timur Tengah, merupakan salah satu efek yang ditimbulkan dari perang mata uang global.
Buku Currency Wars (2011) yang ditulis oleh James Ricards, tidak hanya menjelaskan bagaimana proses berlangsungnya currency wars pasca krisis 2008, namun juga menilisik sejarah dan latar belakang perang tersebut sejak perang mata uang pertama (1921-1936), kedua (1967-1987) dan ketiga yang terjadi sejak tahun 2010. Sejarah dan teori ekonomi moneter dijelaskan dengan runtut dengan gaya bahasa yang mudah difahami.
Motif dari currency wars dapat dijelaskan dengan sederhana. Dalam situasi dimana konsumsi (C) dan investasi (I) melemah, belanja pemerintah (G) terkekang oleh defisit, sementara pajak yang tinggi dan utang yang sudah menggunung beresiko untuk digenjot, maka satu-satunya jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong net ekspor (X-M). Hambatan tarif dan dumping tentu saja berpotensi mendapatkan sanksi dari WTO. Oleh karena itu, salah satu cara yang dianggap mudah dan cepat serta legal adalah mendevaluasi nilai mata uang sehingga harga ekspor menjadi lebih murah di pasar global.
Bagi penulisnya, perang mata uang terjadi ketika standar moneter global tidak bersandar pada standar moneter yang berbasis komoditas riil seperti emas. Standar emas (gold standard) pernah menjadi standar moneter global yang secara resmi berlangsung sejak tahun 1870-1914. Bahkan jauh sebelumnya, emperium Romawi hingga Kekhilafahan Islam telah menggunakan mata uang tersebut.
Dengan standar emas, harga dan nilai mata uang dalam jangka panjang sangat stabil sehingga mampu mendorong pertumbuhan perdagangan dan mobilitas tenaga kerja. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of St Louis, disebutkan bahwa Kinerja ekonomi di Amerika Serikat dan Inggris unggul di bawah standar emas klasik dibandingkan dengan dengan periode berikutnya dibawah mata uang kertas.
Uniknya lagi, standar tersebut tidak membutuhkan perencanaan dan intervensi bank sentral untuk mengontrol sektor moneter. Defisit yang mendorong terjadinya inflasi domestik akan mendorong daya saing ekspor negara tersebut ke negara yang mengalami surplus sehingga secara alamiah mengurangi tekanan inflasi tersebut dan sebaliknya, negara yang surplus perlahan mengalami inflasi yang menurunkan daya saingnya. Mekanisme tersebut di kalangan ekonom disebut dengan price-specie-flow mechanism. Dengan demikian, mekanesme rebalancing akan berjalan secara alamiah, tidak perlu perang urat syaraf sebagaimana yang terjadi antara AS dan Tiongkok selama ini. Oleh karena itu, selama hampir 80 tahun (1836- 1913), perekonomian AS dapat tumbuh kuat meski tanpa kehadiran bank sentral.
Sayangnya, Perang Dunia Pertama, tidak hanya memporak-porandakan tatanan politik, namun juga sistem moneter global. Negara-negara yang terlibat perang tidak lagi menjaga rasio jumlah uang beredar mereka dengan cadangan emas yang mereka miliki, namun dicetak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jerman, misalnya, pada tahun 1921-1924 di masa pemerintahan Weimar ‘menghancurkan’ perekonomian negara tersebut dengan melakukan pencetakan uang besar-besaran untuk membiayai rekonstruksi pasca perang kepada negara-negara pemenang perang. Pemerintah berharap kebijakan inflatoir tersebut mampu meningkatkan pendapatan devisa dari ekspor, wisata dan investasi. Namun celakanya, kebijakan tersebut justru menyebabkan hyperinflasi menghancurkan perekonomian Jerman hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan mata uang reichmark yang baru, yang ditopang oleh emas. Prancis melakukan hal yang sama dengan tujuan agar harga barang ekspornya lebih kompetitif dibandingkan Inggris dan AS sebelum akhirnya kedua negara tersebut melakukan pembalasan. Kondisi tersebut berlangsung hingga berlangsung kesepakatan Bretton Woods.
Pada tahun 1944, AS dan negara-negara Eropa sepakat untuk membentuk tata moneter baru yang dikemudian dikenal dengan perjanjian Bretton Wood yang berlangsung dari tahun 1944-1973. Meskipun pada masa tersebut terjadi resesi, namun secara keseluruhan mata uang negara-engara di dunia relatif stabil, inflasi dan tingkat pengangguran cukup rendah sementara ekonomi tumbuh cukup tinggi. Pada masa tersebut, dolar AS yang diedarkan ditopang oleh emas pada harga di $ 35 per ons. Negara-negara lain menjadikan dolar sebagai back-up atas mata uang yang mereka edarkan. Di saat yang sama, mereka dapat mengkonversi cadangan dolar tersebut sesuai dengan harga yang berlaku. Suatu negara dapat melakukan devaluasi jika mendapat persetujuan dari IMF. Itupun dengan syarat, negara itu mengalami defisit terus menurus yang disertai dengan inflasi tinggi.
Perang mata uang kedua mulai terjadi ketika Inggris berupaya mengatasi pengangguran dengan menambah jumlah uang beredar sehingga berdampak pada peningkatan inflasi. Akibatnya, pound mengalami devaluasi terhadap dolar AS. Di sisi lain, negara-negara seperti Prancis dan Spanyol yang mulai meragukan peran AS sebagai penyangga utama Bretton Woods, menukar cadangan dolar mereka dengan emas. AS dianggap bertindak tidak disiplin ketika melakukan belanja besar-besaran untuk membiayai perang Vietnam dan pembiayaan program belanja sosial Great Society yang dicanangkan oleh Lyndon B. Johnson pada awal 1965.
Konsekuensi dari pelebaran defisit fiskal tersebut, jumlah dolar yang beredar terus meningkat melampaui cadangan emas yang dimiliki AS sehingga membuat harga emas per ounce sebesar US$35 secara riil menjadi terlalu murah. Meskipun demikian, nilanya tetap dipertahankan. Dampak lanjutannya, London gold pool, pasar yang dibentuk untuk menjaga kestabilan harga emas, satu persatu ditinggalkan anggotanya. Upaya IMF untuk menciptakan Special Drawing Right (SDR) juga tidak banyak menyelesaikan masalah, sebab uang kertas tersebut juga tidak ditopang oleh komoditas sama sekali. Celakanya, Presiden AS berikutnya, menghentikan pengkaitan dolar terhadap emas dan melakukan ‘devaluasi’ terhadap dolar dengan mewajibkan pajak sebesar 10 persen terhadap barang-barang impor.
Akhirnya, pada tahun 1973, IMF menyatakan sistem Bretton Woods secara resmi berakhir, nilai mata uang masing-masing negara berfluktuasi satu sama lain dengan mata uang negara lain pada tingkat yang diinginkan pasar atau pemerintah. Peran bank sentral menjadi lebih luas dalam menetapkan seberapa besar nilai tukar yang diinginkan melalui rangkaian otoritas kebijakan yang dimilikinya seperti operasi pasar terbuka, menaikturunkan suku bunga acuan serta kebijakan swap line, pemberian pinjaman mata uang kepada negara lain. Telah banyak negara yang menjadi korban dari kebijakan Bank Sentral tersebut. Sebut saja, "lost (two) decade" yang dialami Jepang sejak tahun 1991 hingga saat ini.
Perang mata uang berlanjut pada tahun 2010. Upaya the Fed melawan deflasi yang terjadi pasca krisis dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga Fed Fund Rate hingga nyaris menyentuh nol persen. Setelah amunisi tersebut dipandang kurang berhasil maka the Fed melancarkan quantitative easing dengan mencetak uang dalam jumlah gigantik. Inflasi memang tidak terjadi pada indeks harga konsumen, namun setelah menciptakan bubble pada harga-harga saham, obligasi, komoditas hingga aset keras lainnya.
Devaluasi mata uang AS sebagai konsekuensi membanjirnya dollar membuat nilai tukar mata uang negara-negara berkembang terapresiasi. Daya saing ekspor mereka melemah sehingga memicu pengangguran. Pembalasan pun dilakukan dengan melakukan berbagai kontrol modal (capital control), pemberian subsidi dan peningkatan bea masuk. Tiongkok berupaya menjaga agar ekspornya tetap tumbuh dengan menerapkan kurs mata uang tetap terhadap dollar AS, yang kemudian melahirkan hubungan politik yang memanas diantara kedua negara.
Belakangan, Bank Sentral Uni Eropa juga melakukan pencetakan Euro besar-besaran untuk meningkatkan likuiditas di negara-negara Eropa yang mengalami krisis. Bank Sentral Jepang juga melakukan hal yang sama dengan menggelontorkan yen untuk meningkatkan inflasi. Harapannya, nilai tukar yen melemah sehingga ekspor negara Sakura tersebut akan terungkit.
Bagi penulisnya, kembali ke standar emas (gold standard) merupakan solusi untuk mengatasi carut-marutnya perang mata uang yang terjadi selama ini. Strategi untuk kembali pada sistem ini terutama bagai AS, juga tidak sulit. Bahkan penulis memaparkan bagaimana langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh oleh AS agar dapat kembali mengaitkan mata uangnya kepada emas. Buku ini sebenarnya lebih banyak mengkritik kelemahan dolar AS, yang celakanya, masih menjadi poros sistem global seluruh mata uang, saham, obligasi, derivatif dan investasi. Tanpa perubahan yang fundamental, AS dan negara-negara yang bergantung pada dollar, harus bersiap menanti krisis yang lebih besar dari tahun 2008. []
